Saturday, December 17, 2011
Angin Tanpa Arah
..............aku disini.....
...........menulis sedikiit kata-kata.....
.....didalam uraian tulisan kertas tisu lusuh......
“Wahai angin, wahai langit-langit hitam dengan awan-awan tanpa hujan…
apakah kau lihat harapan itu seperti cahaya ataukah noktah hitam?”..
“Apakah kau lihat harapan itu adalah cela bagi para pendusta, bagi para pecundang?”
“Doa para pecundang hanyalah kepalsuan bagi realita…”
“Aku ingin melangkah ..seperti layaknya langkah-langkah hewan kecil yang baru dilahirkan oleh sang induk yang sayang padanya”..
“Aku ingin langkahku dipenuhi daun-daun yang menguning karena sudah waktunya untuk musim gugur, karena sudah waktunya kami melihat harapan-harapan baru,”….
” …meskipun kami harus melewati musim dingin,…meskipun kami sudah melewati musim berbunga”….
“Daun-daun hitam dimasa lalu yang ditiupi angin-angin tanpa arah, kini tersimpan di dalam gubuk-gubuk kelam seorang pengembara tua”…
“Semuanya tinggal senyum, semuanya tinggal cerita , semuanya tinggal kenarsisan orang tua…aku berharap untuk menjadi muda dan bisa terus melangkah dengan impian-impian setinggi langit”…
Cih…
cinta
itu
hanya
untuk
pemimpi….
===========
sedikit kutipan dari "lantun angin tanpa arah".
Diposkan oleh
Private!
Saturday, November 26, 2011
Anti Social Media?
Account facebook sudah punya, account twitter sudah punya, tumblr juga punya, blog juga punya (walau kurang eksis), sebenarnya masih ingin belajar social media yang lain, dan memang masih sangat banyak social media lain. Kata teman, "social media itu seperti spion pada mobil, kita bisa tau kondisi di sekeliling mobil kita, tanpa harus bertindak seperti stalker (pengintip /pengintai hidup orang)". Pendapat yang aneh, tapi struktur analoginya cukup konstruktif membuat saya bisa memosisikan diri di dunia social media yang saat ini sudah menjadi cemilan warga Jakarta.
Saya menduga, bisa jadi warga Jakarta di lima tahun terakhir adalah warga Jakarta yang "gemuk" oleh informasi, dan "berkolestrol" karena tertempeli mindset yang macam-macam karena keseringan nyemil social media. Mindset yang sebenarnya "lemak" bagi tubuh, sebenarnya sumber tenaga, tapi tak terolah dengan perbuatan nyata, menumpuk, dan bisa membuat mati. Fisik tak mati, tapi mungkin bisa jadi jiwa kita sebenarnya sudah masuk ke alam barzah.
Terbayang di otak liar ini, fungsi tubuh sepenuhnya dikontrol oleh koordinasi lima indera, tanpa hati. Otak hanya akan menjadi operator yang menjalankan mesin-mesin pengolah referensi. Panca indera menjadi senjata ampuh yang diberikan Tuhan muntuk mendukung pencapaian kita. Panca indera membantu kita dalam mencengkeram ide-ide, dan mimpi untuk memiliki. Rasa ingin memiliki, itulah yang dihasilkan dari koordinasi kelima indera ini. Rasa untuk menguasai kapital, itulah yang seringkali menghinggapi orang-orang yang di otaknya hanya berisi program-program pencapaian.
Lalu dimanakah letaknya hati? ya posisinya tak pernah berubah, selalu menemani usus. Hati versi bangsa ini adalah hati yang sejajar dengan perut. Hati versi samawi (nasrani, islam, yahudi) adalah heart, qalbu, yang sebenarnya adalah jantung, pemompa darah. Heart is not liver. Ia diposisikan di atas perut, dan sejajar dengan paru-paru sebagai alat bernafas. Pengistilahan ini membuat pikiran saya mengembara, apakah betul bangsa Indonesia ini bangsa artifisial? Bangsa yang mudah disuguhi materi? Karena kalbu disejajarkan dengan perut?...
Kembali ke social media. Saya melihat sebuah fenomena, kaum muda Gerindra mulai "melirik" strategi untuk "memusuhi" social media. Link-nya bisa dilihat disini . Sebetulnya tidak benar-benar memusuhi, hanya memosisikan diri. Social media memang senjata ampuh untuk mencapai interkolektifitas. Sebuah cara untuk menjadi keluarga besar yang menghargai pentingnya kapitalisasi ide. Tapi tetap, individu adalah sebuah sosok yang dihidupkan oleh qalbu. Berserah diri pada referensi, hanya akan membuat kita mayat-mayat berjalan. Normatif, templatis, dan tak bersuara melawan kapitalis. Qalbu seolah hanya bisa bersuara di alam barzah, ya karena qalbu budak-budak materialis seringkali telah mati.
Social media adalah privilege individu bebas. Tapi bukanlah tujuan. Social media hanyalah batang-batang korek yang membakar individu sejati agar menjadi dirinya sendiri, yang punya hati, yang punya jiwa, dan yang membesarkan semesta, yang membelenggu ego-ego kesombongan atom-atom jagad raya. Kesombongan yang seharusnya tak tampak dari individu yang merdeka. Merdeka untuk berbagi, dan berhati untuk memiliki.
Diposkan oleh
Private!
Monday, November 07, 2011
Sunday, October 23, 2011
Berkarya Tanpa Tersandera?
Memulai karya baru seringkali adalah pekerjaan yang maha berat. Berat karena memang benar-benar harus baru, seperti tanpa keterkaitan dengan karya-karya sebelumnya. Karya baru itu pun berat karena seolah kita harus terlepas dari keterjebakan sentuhan diri kita pada masa lalu.
Hal ini terjadi pada saya dahulu, dan terjadi juga dengan rekan saya, sesama makhluk pembenci hal-hal normatif. Tumben rasanya saya mendapatkan waktu untuk mendengarkan apresiasi darinya, tentang posisi dirinya saat ini. Kata lain "curhat" yang keduluan populer. Istilah curhat agak tak saya sukai, karena seringkali kata curhat menjebak kita untuk subjektif memandang orang.
Ia memulai sesi apresiasi tentang dirinya, dan saya tinggal menikmati. Ia mengapresiasi dirinya yang berada dalam lembah kejenuhan, setelah berkarya hampir setahun di Jakarta. Ia takut dirinya akan memproduksi karya yang "begitu-begitu" saja, gampang tertebak, membludak ke dalam imaji dan gerbang niatnya. "Saya stuck, apa yang harus saya perbuat?" sebuah apresiasi yang diakhiri tanda tanya. Ia bertanya pada saya, yang terus terang saat itu terhenyak karena belum siap menjawab.
Saya berusaha tersenyum. Tersenyum adalah bentuk jawaban yang biasa saya pertama kali lakukan sebelum berkata. Senyuman bisa berjuta makna, layaknya lukisan Monalisa. Satu hal yang pasti adalah senyuman bisa jadi obat, mungkin untuk dia, dan yang pasti untuk saya. Butuh kurang lebih 10 detik untuk saya mencari kata-kata jawaban yang tepat. Karena urusan niat berkarya adalah urusan yang sangat subjektif, namun berdampak pada objective (tujuan) hidup kita.
"Coba Lu pilah lagi urusan lu, mana yang rutin, mana yang benar-benar berkarya," ujar saya. Rutinitas seringkali meninggalkan kesan seperti kita sedang mengisi check list daftar pekerjaan yang nyata-nyata berulang. Sedangkan karya seringkali membutuhkan energi untuk mencari "wangsit" atau petunjuk dari alam, menghaluskannya dalam coretan ide, mengolahnya dalam sistem yang bertumbuh, dan membungkusnya dengan kesan dan referensi terakhir kita. Berkarya itu seperti menjadikan kita seolah Tuhan, sebuah aktivitas yang agak arogan untuk skala manusia. Namun dengan karyalah kita bisa menunjukkan bahwa kita bukanlah Tuhan. Kita hanya 0/1 nya Tuhan. Rasa lelah dan kehilangan orientasi akan muncul saat kita selesai menyelesaikan sebuah "karya",adalah bukti yang membuktikan bahwa manusia punya batasan. Batasan karya, sesuatu yang sangat manusiawi.
Apa yang dilakukan rekan desainer lainnya saya ceritakan sebagai referensi. Rekan desainer tersebut punya ritual rutin saat telah menyelesaikan sebuah proyek bangunan. Ia akan serius untuk berlibur dan seraya menyerap simbol-simbol alam yang baru. Rekan yang saya ceritakan itu menginvestasikan 50%waktu bekerjanya untuk mengisi ulang energi badannya yang tersalur ke karya terakhirnya. Tak heran setiap karyanya seolah memiliki aura, tak datar seperti wajah pengantin yang tak ikhlas dikawin.
"Lu harus cari waktu untuk kembali ke alam, kembali ke haribaan Ilahi dan mendapatkan simbol dan energi baru," ujar saya berkata sambil terpejam. Terpejam karena pembicaraan ini terjadi setelah saya belum tidur selama 36jam. Selain itu, untuk urusan memberi petuah, saya berusaha menghilangkan peran indera saya. Saya berusaha menggali suara-suara berisik di dalam tubuh, yang seringkali berkata. Suara tubuh yang ternyata adalah suara hati.
"Gue tau lu baru saja menyelesaikan beberapa karya idealis secara beruntun. Ga heran lah kalo kejadian "kopong ide" ini terjadi. Kerja itu rutinitas, karya itu penciptaan entitas. Jangan meremehkan badan kita saat berkarya," ucapan saya meluncur deras seperti orang sok tahu. Tapi saya yakin dengan ucapan saya itu. Saya yakin dengan kesoktahuan saya saat berhasil mendengar suara hati.
"Oke, saya akan cari waktu," ujarnya. Kami pun melanjutkan dengan cerita-cerita hantu. Sebuah cara tersingkat untuk mengurangi keterkaitan dengan ruang dan waktu. Sebuah cara yang singkat juga untuk menghargai daging yang telah membantu ruh ini melewati hari.*
*Teringat dengan lagu Sujiwo Tejo ~Cinta tanpa Tanda, dan ucapannya di twitter: ""Bunuh" panca inderamu, dan rasakan cinta tanpa tanda. Selamat mengarungi cinta yang tanpa tanda".
Diposkan oleh
Private!
Thursday, May 26, 2011
Apakah Kita Masih Butuh Politik?
Di antara cerita perang yang terjadi di hutan-hutan, perkotaan, air, darat, gunung, dan lembah, bangsa Indonesia ternyata terlahir melalui perdebatan, melalui diskusi, dan olah pikir. Tak ada aturan dalam debat saat itu, hanya rasa ingin mendapatkan makna baru dan pelepasan cita-citalah yang membuat tokoh bangsa mengumpulkan semua ego mereka yang berbeda-beda. Kesepakatan menjadi orientasi dalam menyelesaikan masalah bangsa.
Kesepakatan itu berjudul undang-undang dasar, dan mungkin masih banyak kekurangannya. Seperti payung kecil, kadang tak cukup menaungi warganegara yang ingin mendapatkan kenyamanan. yak, kenyamanan, bukan kemerdekaan. Bagi orang yang mencari merdeka, memiliki payung saja sudah menjadi anugerah. Memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi hujan adalah sebuah amanah. Kenyamanan adalah candu bagi orang yang ingin dimanjakan mimpi.
Mulai dari Undang-Undang, sistem dan organisasi pun tumbuh, tumbuh seperti syaraf otak yang saling tersambung, dan menjadi mesin fikir dalam menyelesaikan masalah kebangsaan. Peraturan tumbuh seperti jalan-jalan raya kota yang saling menghubungkan. Besar, kecil, panjang, lebar, sempit, luas, seperti itulah analoginya.
Setiap orang selayaknya bisa menggunakan jalan itu. Tak haruslah kita menggunakan kendaraan jika tak terikat dengan timeline waktu. Cukup berjalan saja, kita bisa sampai di tujuan, kita bisa mendapatkan rasa kemerdekaan dan keadilan.
Apa yang terjadi di pusat ibukota ini sungguh seperti komedi. Tak usahlah dianggap tragedi, jika kita masih memiliki solusi dan bayangan indah untuk membuat dunia jadi lebih indah. Mesin-mesin politik mengisi jalan-jalan ibukota hingga ruas terkecil. Itu bukan masalah. Yang jadi masalah adalah pengemudinya tak tau cara menggunakan mobil. pejalan kaki tak ada lagi, karena pasti tergilas. Mobil besar, mobil kecil, saling berebutan ingin menikmati jalan tanpa gangguan, agar bisa sampai tujuan.
Sebenarnya apa sih arti tujuan, jika akhirnya kita harus mengorbankan jalan yang saling terhubung itu jadi tanpa arah, dan membuat frustasi. Sebenarnya apa sih arti tujuan, jika kita tak bisa berbagi. Nihil... dan memiliki kemampuan terbang, kini menjadi mimpi para politisi-politisi yang tak bisa berkendara...
Diposkan oleh
Private!
Friday, February 11, 2011
Haruskah Kita Memahami Jakarta?
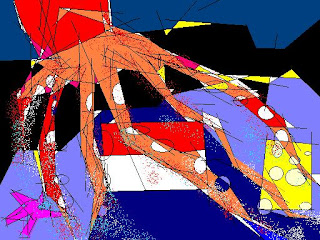
Kemarin saya bertemu dengan teman saya yang sedang bingung. Bingung antara bahagia atau khawatir. Anaknya kini lebih percaya sponge bob untuk dijadikan ibunya. Ibunya seorang pekerja media di ibukota, tinggal di "samping" Jakarta, dan mungkin melihat anaknya adalah sebuah pertunjukkan terindah di setiap harinya. Namun saya rasa pertunjukkan yang dibawakan oleh sang Anak di hari itu membuat sang ibu berkendara dengan keterkejutan...
Ada variabel berpikir menarik yang saya dapatkan dari anak tercinta rekan saya ini. Bahwa untuk merasakan dan memahami proses hidup, seringkali kita ga butuh itu namanya pengajaran. Ide spongebob menjadi ibu bagai kembang api di tengah kegelapan. Keliaran indera dan ekplosifnya cara anak mengembangkan daya paham bagaikan mata air inspirasi kita..
Ruang, dengan segala karakteristiknya, mewadahi raga dan barang-barang milik kita. Begitu pula dengan pikiran, dengan segala variabel yang dipikirkannya, menjadi pencetus gerakan kita. Namun, hal itu menjadi tak berbentuk, tak bisa dipahami, saat kita memainkan runutan (timeline) waktunya secara acak. Semua tatanan ruang, dan tatanan pikir jadi tak ada artinya...
Pemahaman seperti itulah yang saya pahami dulu... Tapi cerita rekan saya ini justru membuyarkan pemahaman tersebut. Anak bisa memahami sesuatu secara utuh, tanpa harus melalui proses runut yang biasa kita lakukan saat belajar.
Mentransformasi pikirannya menjadi simbol yang ada di kamar. Itulah kemampuan lebih sang anak. Sang Anak begitu inspiratif untuk membuat pikirannya menjadi simpel, namun tetap nyaman dipandang. Anak melihat pikirannya bertansformasi menjadi sosok-sosok utama yang mengisi cerita hariannya. Atau bisa juga simplifikasi pemikirannya terlihat seperti bibit pohon. Bibit ini bisa jadi apa saja saat ia membayangkan proses tumbuh besar sang pohon. Inilah yang membedakan anak kecil dan orang dewasa. Orang dewasa seringkali terpancing untuk menggeneralisir sebuah fenomena agar mudah dihapal dan mudah diarahkan.
Menggeneralisir adalah sebuah fenomena yang membuat sebuah fenomena "seolah" tertangkap dalam satu simbol. fenomena terlihat seperti pohon besar yang terserabut dari tempatnya, dan disimpan dalam memori. Akar pohon yang begitu kompleks menyebar di tanah tak menjadi kepeduliannya. Menggeneralisir fenomena seringkali menimbulkan persoalan. Karena simbol tidak dijelaskan lagi secara utuh.
Lalu apa hubungannya dengan judul blog ini?... ya karena terlalu banyak fenomena yang digeneralisir dalam simbol-simbol. Dan terlalu banyak persoalan yang ditimbulkan oleh simbol-simbol akibat generalisasi ini. Ini nih contohnya:... Ormas dengan simbol agama, pekerja sehat dengan simbol bike to work, Macet jakarta dengan simbol PaMer PaHa nya... Simbol-simbol ini justru mematikan rasa kita pada keterkaitan waktu. Ingin lari rasanya dari masalah ormas agama dengan isi orang-orang penuh nafsu... Boro-boro ingin mengembangkan cerita yang indah dari simbol-simbol yang ada. Justru hanya ada cerita sinis dan pencarian kambing hitam..
Saya jadi bahagia saat mencoba membuat simplifikasi Jakarta. Yak, saya bayangkan Jakarta seperti paul gurita. Gurita yang memiliki banyak kaki (kemampuan), dan bisa meramal (kelebihan) untuk kemenangan kompetisi-kompetisi yang akan terjadi.. Namun betapa tak solutifnya otak saya saat harus menggeneralisir Jakarta dengan simbol benang kusut... hehehe
Simplify..yes.. Generalize.. no
Diposkan oleh
Private!
Sunday, January 30, 2011
Hibernasi...ah..

"Realita seolah tak berarti saat mimpi tak sanggup untuk hadir".... Nnngg...itu bahasa galau yang keluar dari rekan saya. Ia telah bergadang kurang lebih empat hari lamanya. Nggak kebayang bisa seperti itu.. Tapi itulah kenyataan yang saya dapatkan.
Menurut saya, lelah juga rasanya kalo kita selalu hidup dan memanfaatkan panca indera tanpa waktu istirahat. Sepertinya diam itu perlu,karena saat diam kita bisa merasakan mimpi.
Mungkin inilah permainan yang diajarkan Tuhan, nama lengkapnya permainan dinamika hidup. Tuhan memberikan keseimbangan dari semua aspek hidup. Tuhan juga seringkali hadir pada saat kita merasa seimbang. begitu banyak inspirasi yang hadir saat kita berada dalam posisi seimbang. Setiap perbedaan seolah meberikan makna,dan itu adalah inspirasi.
Saya pernah juga mencoba untuk bergadang lebih dari dua hari. Suer, bukan puas dengan hasil kerja yang didapatkan. Kelelahannya menghilangkan interest saya pada apa yang saya lakukan. Dulu, sebelum kerja di media saya adalah seorang creative di event organizer. Namanya terdengar keren, tapi saya membayangkannya seperti kerjaan yang benar benar melelahkan otak. Kerja saya adalah mempersiapkian proposal, menyiapkan publikasi,dan desain panggung untuk event band dan tour band. 3inone. Boro-boro menikmati band yang manggung.. kerja saya adalah mempersiapkan panggung di malam hingga pagi hari, lalu siangnya tidur karena kelelahan, dan bangun malam saat konser usai, pengen nonton, tapi badan tak bisa dipaksa kompromi.Begitu terus selama hampir setahun.
Hmm, bayangkan saja otak yang diberi handuk karena terlalu banyak cairan otak yang terpakai untuk dijadikan energi berpikir.... Lebay terdengarnya, tapi itulah pelajaran berharga yang saking mahalnya ga akan saya beli lagi... :D
Betapa istirahat itu mahal, saat kita melewati proses yang wajar. Bagi saya, istirahat adalah investasi untuk tubuh, inspirasi untuk mimpi, dan tentunya menurunkan kerja otak yang fluktuatif.
Diposkan oleh
Private!
Monday, January 24, 2011
Melintasi Jakarta Tanpa Peluh

Akhirnya...
Hampir empat bulan saya membisu untuk menuliskan kata-kata di udara Jakarta... oh.. saya sudah tidak di jakarta. Terhitung 5 Desember 2010 kemarin, saya telah pindah ke kawasan Japos,Tangerang, surganya para pekerja sub urban ibukota.
Kelahiran anak membuat saya bahagia, namun itu adalah kebahagiaan yang tak bisa terbungkus dalam kata-kata. Terlalu banyak bahagia itu, terlalu banyak judul yang harus saya buat hingga saya merasa, menuliskan kebahagiaan tentang anak bisa-bisa jadi bahagia yang basa basi.
Seperti kata orang galau di halte enam bulan yang lalu, "cinta itu perbuatan, pengorbanan, sama sekali bukan kata-kata"... Itulah yang membuat saya berada dalam dunia kontradiksi untuk curhat dalam kata-kata cinta, empat bulan ini ..
Bahagia, kesal dengan dinamika politik kantor, membuat saya justru fokus memikirkan hal-hal yang bersifat formal. Tugas ya dikerjakan, rencana ya dijalankan. Empat bulan saya tak banyak melakukan hal-hal yang nakal. Nakal, diluar alur perputaran otak. Menulis di blog ini adalah sebuah hal yang nakal...Huh, terasa bukan di tulisan saya ini, empat bulan tak nge-blog membuat tulisan begitu formal, tidak nakal...
Alhamdulillah..
Akhirnya cerita baru pun tertulis...
Kenakalan itu bisa jadi hal yang formal...ternyata..
Tuhan mengirimkan "kenakalan" itu pada saya tadi pagi, dalam bentuk kisah nyata sang penjual bubur.
Istri saya yang supel, menggemari bubur ayam yang dijual di gerobak motor. Motor bergerobak tepatnya. Rasanya enak, ada tongcai (wortel kering yang asin) ala makanan Cina. Enak bukan karena bubur ayam yang bergerobak standar, yang dijual sebelum tukang bubur bermotor ini datang, rasanya seperti air payau. Tapi karena memang bumbunya meresap.
Bubur meresap membutuhkan waktu. rasanya yang enak menimbulkan rasa ingin tahu. Istri saya pun bertanya, "Mas, tinggal di mana, kok bisa siang terus jualannya?," ... "Saya dari Tambun, Mbak"... "Tambun? Bekasi? Jauh tuh Mas"... "Ya mau gimana lagi Mbak, namanya cari uang"... pembicaraan terhenti, karena istri saya masih takjub membayangkan jarak jauhnya...
Perjalanan sang tukang bubur, dari Tambun ke Tangerang adalah sebuah perjalanan yang mungkin melelahkan baginya. Namun peluhnya sudah dibungkus dalam kata-kata, "ya mu gimana lagi mbak, namanya cari uang." Peluhnya adalah sebuah kata-kata kepasrahan.
Saya tak tahu pasti, keterkaitan rasa yang enak itu dengan perjalanan jauhnya. Saya tak tahu pasti, bisa-bisanya kota Jakarta tak lagi jadi target tempat berjual bubur baginya. Ia melintasi Jakarta. Tapi ia tak mencari Jakarta... jakarta kelewatan baginya... Jakarta hanyalah sebuah lintasan waktu.. yang mungkin membantu menggurihkan ramuan buburnya...
Diposkan oleh
Private!
Subscribe to:
Posts (Atom)











